Tarian maut bunga kuburan
Hutan larangan Ale’ Mali’ kembali diselimuti keheningan yang mencekam setelah gema runtuhnya batu cadas perlahan lenyap ditelan kegelapan. Namun, bagi pemuda yang kini menyeret langkahnya di atas lumpur becek, keheningan itu bukanlah pertanda damai. Itu adalah keheningan semu, laksana tarikan napas panjang seekor ular sanca sebelum membelit mangsanya hingga remuk.
Langkah kaki si pemuda semakin berat, seolah-olah bumi menolak untuk dipijak. Rasa nyeri di betis kanannya kini telah berubah wujud menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bukan lagi sekadar perih sayatan Bessi Poka-Poka, melainkan sensasi panas membara yang menjalar liar menelusuri pembuluh darah, laksana aliran lahar gunung berapi yang sedang mencari jalan untuk meledakkan jantung.
Ia berhenti sejenak, menyandarkan bahunya yang gemetar pada batang pohon damar yang dingin berlumut. Napasnya tersengal-sengal, uap putih tipis keluar dari mulutnya di udara malam yang lembap. Dengan tangan yang mulai kehilangan rasa, ia menyingkap kain lipa’ sabbe yang membebat lukanya dengan hati-hati.
Mata tajamnya membelalak di bawah sorot cahaya bulan yang remang-remang.
Darah yang merembes dari balutan kain itu tidak lagi berwarna merah segar, melainkan merah kehitaman, kental seperti bubur asPal, dan sedikit berbuih. Bau anyir yang menguar dari sana bercampur dengan aroma hangus yang aneh—tanda khas bekerjanya racun jahat yang sangat ditakuti di tanah selatan.
“Racun Waru Pepe’…” desisnya pelan, menahan gejolak di dada.
Ia menggeleng lemah. Rupanya si Jagal bertopeng besi tadi menyimpan kelicikan di balik otot kawatnya. Gada besi raksasa itu pasti telah direndam dalam getah pohon waru beracun yang tumbuh di kawah belerang panas. Musuhnya memang berniat membunuhnya perlahan jika pukulan langsung gagal meremukkan tulangnya. Racun itu kini mulai merayap naik, membekukan aliran darah sembari membakar organ dalam. Jika sampai ke jantung, tamatlah riwayatnya; darah akan mendidih dan nyawanya akan melayang sia-sia.
Tangannya merogoh kantong kulit rusa yang terikat di pinggang, mencari-cari sisa penawar racun yang mungkin masih terselip. Jari-jarinya hanya menyentuh dasar kantong yang kosong. Hanya tersisa remah-remah tembakau kering dan debu halus.
“Celaka…” keluhnya dalam hati. Tidak ada umpatan kasar yang keluar dari bibirnya, sebab seorang pewaris ilmu sejati pantang mengotori lidahnya dengan kata-kata nista di saat genting. Kepanikan hanya akan mempercepat kerja racun.
“Heh heh heh… Mencari ini, Anak Muda?”
Suara tawa itu terdengar ringan, renyah, namun menusuk telinga seperti gesekan bambu kering di tengah malam buta. Anehnya, suara itu tidak datang dari depan, bukan pula dari belakang, melainkan turun dari atas langit-langit hutan.
Si pemuda mendongak waspada, mengabaikan rasa sakit yang menghantam lehernya. Tangan kanannya kembali mencengkeram hulu badik Pallipu Alang, siap untuk pertarungan terakhir meski tenaganya tinggal ampas.
Di atas dahan pohon damar itu, sekitar tiga tombak dari tanah, duduk sesosok manusia dengan santai. Kakinya berayun-ayun seolah sedang duduk menikmati sore di teras rumah panggung, bukan di tengah hutan keramat yang penuh maut.
Orang itu mengenakan jubah putih kedodoran yang tampak bercahaya di bawah sinar bulan, kontras dengan kegelapan hutan yang pekat. Wajahnya tertutup caping lebar dari anyaman bambu hitam, membuat wajahnya tersembunyi dalam bayangan kelam. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah botol kecil dari tanah liat, menggoyang-goyangkannya dengan nada mengejek.
Klecuk… klecuk… Bunyi cairan di dalam botol itu terdengar jelas, seolah mengejek kerongkongan si pemuda yang kering kerontang.
“Siapa Ki’?” tanya si pemuda tegas. Suaranya serak menahan sakit, namun sorot matanya tetap tajam laksana elang yang terluka.
Sosok itu melompat turun. Gerakannya seringan kapas yang ditiup angin.
Wuuuttt… Tap!
Kakinya mendarat di tanah becek tanpa menimbulkan cipratan lumpur sedikit pun. Bahkan rumput kering di bawah kakinya tidak patah. Ini adalah pertunjukan ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi yang disebut Langkah Awan Berarak, ilmu langka yang konon hanya dikuasai oleh segelintir pendekar tua dari wilayah pegunungan Latimojong.
Perlahan, sosok itu mengangkat wajahnya. Di balik caping itu, terlihat wajah seorang kakek tua dengan jenggot putih panjang yang dikepang dua, menjuntai hingga ke dada. Kulit wajahnya masih kencang dan kemerahan seperti bayi, namun matanya bersinar jenaka sekaligus liar, menyimpan kegilaan yang tak tertebak. Yang Paling mencolok adalah telinga kanannya yang memakai anting besar berbentuk tengkorak emas, sementara telinga kirinya tampak cacat, seolah pernah ditebas putus separuh.
“Orang-orang di dunia persilatan memanggilku Puang Parungu,” kekeh kakek itu sambil mengelus jenggot kepangnya. “Tapi kau boleh memanggilku Kakek Penolong… asalkan kau mau menjadi anak manis yang menurut.”
Si pemuda menyipitkan mata. Ingatannya berputar cepat. Ia pernah mendengar nama itu dalam cerita-cerita para pedagang di pelabuhan. Puang Parungu (Sang Pendengar). Seorang tabib nyentrik sekaligus pembunuh bayaran yang konon bisa mendengar suara jatuhnya jarum dari jarak satu Pal¹. Kabarnya, ia bisa menyambung kePala putus asalkan belum lewat satu tarikan napas, tapi bayarannya seringkali tidak masuk akal—kadang nyawa, kadang pusaka keramat.
“Aku tidak punya waktu bermain teka-teki, Orang Tua. Jika itu penawarnya, sebutkan harganya. Jika bukan, minggir dari jalanku,” ujar si pemuda tenang, mencoba mengatur napas prana untuk menekan racun.
Puang Parungu tertawa terbahak-bahak hingga tubuh kurusnya berguncang. Suara tawanya mengandung tenaga dalam yang aneh, membuat gendang telinga si pemuda berdenging sakit, seolah ditusuk jarum halus.
“Harganya? Heh heh heh. Kau lucu, Nak. Lucu sekali! Tubuhmu sudah separuh masuk liang kubur, tapi bicaramu masih sombong seperti raja. Kau pikir kau bisa membeli nyawamu dengan uang?”
Si pemuda sadar orang tua ini benar. Tenaganya sudah terkuras habis melawan Barata tadi. Pandangannya mulai berbayang ganda. Racun itu bekerja cepat, melumpuhkan syaraf geraknya satu per satu.
“Apa mau Ki’?” tanyanya akhirnya, merendahkan nada suaranya, mencoba menawar waktu.
Puang Parungu berhenti tertawa. Wajah jenakanya tiba-tiba berubah serius, dingin, dan tajam. Aura membunuh yang tipis namun pekat menguar dari tubuh rentanya, membuat udara di sekitar mereka terasa turun suhunya secara drastis.
“Barakkang tidak hanya mengirim si Gajah Dungu Barata,” bisik kakek itu, suaranya kini berdesis seperti ular sanca. “Ada tiga pembunuh lagi yang sedang menyisir hutan ini. Si Kembar Belati Setan dari Timur, dan seseorang yang baunya amis seperti bunga kuburan…”
Si pemuda terdiam. Nama-nama itu adalah mimpi buruk di dunia persilatan tanah Celebes. Mereka adalah para pencabut nyawa yang tidak pernah gagal menuntaskan tugas.
“Aku akan memberikan penawar ini,” lanjut si kakek sambil melempar botol tanah liat itu ke udara dan menangkapnya lagi dengan gerakan kilat. “Tapi ada harganya. Bukan emas, bukan permata. Aku sudah bosan dengan benda-benda duniawi itu.”
“Katakan,” sahut si pemuda.
“Kitab Lontara’ Hitam milik gurumu, Puang Lallo. Aku tahu benda itu tidak ikut terbakar saat bengkelnya dihancurkan. Kau membawanya, bukan? Telingaku bisa mendengar gesekan daun lontar kering di balik baju bela dada-mu setiap kali kau bernapas.”
Darah si pemuda berdesir. Bagaimana orang tua ini bisa tahu sedetail itu? Kitab pusaka itu terselip rapi di balik bebat kain di dadanya, berisi rahasia tempaan senjata pusaka dan ilmu pengobatan kuno yang bisa mengguncang kerajaan jika jatuh ke tangan yang salah.
Ia menimbang untung rugi. Memberikan kitab itu sama saja mengkhianati amanat gurunya, sebuah tindakan *Mappakasiri’*² yang lebih buruk dari kematian. Tapi mati di sini berarti kitab itu akan jatuh ke tangan Barakkang atau siapa pun yang menemukannya mayatnya nanti.
“Aku tidak membawanya. Kitab itu sudah musnah menjadi abu,” dusta si pemuda dengan wajah datar, mengerahkan cipta rasa untuk menenangkan detak jantungnya agar tidak terdeteksi oleh telinga sakti si kakek.
“Bohong!”
Tiba-tiba, Puang Parungu mengibaskan lengan jubahnya yang lebar.
Breettt!
Angin pukulan jarak jauh yang padat dan tak kasat mata menyambar dada si pemuda. Serangan itu disebut Tamparan Bayu Tanpa Rupa.
Si pemuda tak sempat menghindar karena kakinya yang kaku. Tubuhnya terpental ke belakang laksana daun kering ditiup badai, menabrak pohon di belakangnya dengan keras.
“Ukh!”
Ia terbatuk darah. Kain pembungkus di dadanya sedikit tersingkap akibat hantaman itu, memperlihatkan ujung naskah daun lontar tua yang berwarna kecokelatan.
“Mataku mungkin tua, tapi telingaku bisa mendengar kebohongan dalam aliran darahmu,” seringai kakek itu. Ia melangkah maju perlahan, langkahnya mengambang tidak memijak bumi. “Serahkan. Atau kubiarkan racun itu membuatmu memohon kematian sambil merangkak mencium tanah.”
Buronan muda itu memegang dadanya yang sesak. Tulang rusuknya terasa retak. Pilihan yang sulit. Memberikan kitab berarti hidup tapi menanggung malu seumur hidup, mempertahankannya berarti mati konyol di tempat sepi ini.
Namun, di saat kritis itu, telinganya yang juga terlatih menangkap suara lain. Suara yang sangat halus, jauh lebih halus dari desau angin. Suara desingan logam tipis yang membelah udara dari arah semak belukar di belakang si kakek.
Bukan serangan untuknya.
“AWAS!” teriaknya refleks. Meski musuh, naluri pendekarnya tidak bisa membiarkan serangan bokongan yang curang.
Puang Parungu, meski sakti, rupanya terlalu asyik mengintimidasi mangsanya. Teriakan itu membuatnya menoleh sepersekian detik.
Crrrasss!
Sebuah selendang sutra merah melesat dari kegelapan laksana lidah api, membelit leher si kakek dengan kecepatan yang tak bisa diikuti mata biasa. Di ujung selendang itu terdapat pemberat berupa bola besi berduri kecil.
“Hukk!” Mata kakek itu terbelalak.
Dari balik bayangan pohon beringin, muncul sosok wanita yang kecantikannya mampu membuat bulan merasa malu, namun auranya mematikan. Ia mengenakan Baju Bodo³ berwarna hitam ketat yang memamerkan lekuk tubuh, dipadu dengan sarung sutra merah darah. Wajahnya putih pucat seperti mayat, bibirnya merah menyala karena sirih. Rambutnya disanggul tinggi dengan hiasan tusuk konde emas berbentuk kelabang.
Ia tersenyum manis, namun senyum itu lebih mengerikan daripada seringai topeng besi Barata.
“Janganki serakah, Puang Tua…” suara wanita itu mendayu-dayu, merdu seperti nyanyian pengantar tidur, namun mengandung tenaga dalam yang membius. “KePala pemuda itu, dan kitab yang dibawanya, sudah dipesan oleh Puang Barakkang untukku. Sebaiknya Puang kembali mengurusi pasien bisul di kampung.”
Itu dia. Daeng Bunga, yang berjuluk Bunga Jera’ (Bunga Kuburan). Pembunuh wanita Paling ditakuti yang membunuh korbannya sambil menari.
Puang Parungu meronta, wajahnya memerah. Ia mencoba melepaskan jeratan selendang di lehernya, tapi wanita itu menyentakkan tangannya dengan gerakan tarian Pakarena⁴ yang gemulai namun bertenaga raksasa. Selendang menegang kaku seperti batang besi.
“Dasar Perempuan Gila!” maki si kakek dengan suara tercekik.
Tangannya bergerak cepat, jari-jarinya menekuk membentuk cakar, lalu ia menghantamkan telapak tangannya ke arah selendang itu.
Plak!
Tenaga dalam Guntur Memecah Karang dilepaskan. Selendang sutra itu bergetar hebat, tapi tidak putus. Sutra itu rupanya ditenun dengan campuran benang emas dan serat ulat sutra racun dari tanah Toraja.
Akibat guncangan itu, botol penawar racun di tangan kiri si kakek terlepas. Botol tanah liat itu melayang di udara, berputar-putar lambat di bawah sinar bulan.
Waktu seakan melambat bagi si pemuda.
Botol itu adalah nyawanya. Jika botol itu jatuh dan pecah di atas batu, tamatlah dia. Tidak ada kesempatan kedua.
Mengabaikan rasa sakit yang membakar kakinya dan tulang rusuknya yang nyeri, ia mengerahkan sisa tenaga terakhirnya. Ia tidak menerjang musuh. Ia melompat menjatuhkan diri, meluncur di tanah becek seperti biawak, menjulurkan tangannya ke arah jatuhnya botol.
Mata Daeng Bunga berkilat. Ia melihat gerakan buruannya. Tangan kirinya yang bebas bergerak, kali ini mengirimkan tiga buah jarum perak halus ke arah pemuda itu untuk mencegahnya.
“Jangan harap, Tikus!”
Wuuut! Wuuut! Wuuut!
Pemuda itu melihat jarum-jarum maut itu datang. Jarum Peteppu’⁵ yang terkenal tak berbunyi tapi mematikan. Di saat yang sama, botol penawar tinggal sejengkal dari tanah berbatu.
Ia harus memilih: Menghindar dan kehilangan penawar, atau mengambil penawar dan menerima tusukan jarum.
Batinnya jernih. Mati karena racun jarum atau mati karena racun gada, sama saja. Tapi setidaknya kalau ia memegang penawar, ia punya satu harapan.
Ia menggertakkan gigi. “Demi Kehormatan Guru!”
Ia tidak menghindar. Ia terus meluncur. Tangannya menyambar botol itu tepat sebelum menyentuh batu.
Crap!
Dapat!
Tapi…
Jleb! Jleb!
Dua jarum perak menancap telak di bahu kirinya. Satu jarum lagi meleset, menancap di tanah.
“Argh!” Ia mengerang tertahan. Rasa dingin yang menusuk tulang langsung menyebar dari bahunya, bertarung dengan rasa panas di kakinya.
Dunia berputar hebat. Kini ada dua racun berbeda yang bertarung di dalam tubuhnya laksana dua naga yang berebut wilayah kekuasaan. Ia terguling di tanah, mendekap botol itu erat-erat di dadanya, sementara di hadapannya, pertarungan dua raksasa silat itu meledak.
“Kau merusak mainanku, Nenek Sihir!” teriak Puang Parungu yang akhirnya berhasil melepaskan jeratan selendang dengan merobeknya menggunakan pisau kecil yang tersembunyi di balik lengan baju.
“Mulutmu perlu dijahit, Kakek Bau Tanah!” balas Daeng Bunga.
Wanita itu melompat ke udara, tubuhnya berputar indah. Kain sarungnya berkibar-kibar. Dari balik kibaran kain itu, melesat puluhan jarum perak laksana hujan gerimis maut.
Ting! Ting! Trang!
Si kakek tidak tinggal diam. Ia mencabut kipas besinya, memutarnya di depan dada membentuk perisai. Jarum-jarum itu terpental berjatuhan mengenai batang pohon hingga berasap.
Si pemuda memanfaatkan kekacauan itu. Dengan tangan gemetar hebat, ia mencabut sumbat botol tanah liat itu dengan giginya. Plop.
Bau cairan itu busuk, seperti telur busuk dicampur empedu ular. Tanpa pikir panjang, ia menenggak isinya.
Glek… glek…
Rasanya pahit luar biasa, membuat perutnya bergolak ingin muntah. Tapi ia menahannya. Ia memaksanya turun ke lambung.
Sesaat tidak terjadi apa-apa. Lalu, tiba-tiba hawa sejuk yang luar biasa menjalar dari perutnya, menyebar ke seluruh tubuh, memadamkan api di kakinya dan mengusir hawa dingin di bahunya. Rasa sakitnya mereda perlahan, digantikan oleh rasa lemas yang luar biasa.
Ia selamat dari racun. Untuk sementara.
Namun, ia masih berada di kandang macan. Dua pembunuh wahid itu masih bertarung sengit, saling bertukar jurus maut. Pohon-pohon di sekitar mereka mulai tumbang satu per satu terkena hantaman tenaga dalam yang nyasar.
Pemuda itu mencoba bangkit, tapi kakinya masih lemas seperti agar-agar. Ia harus mencari cara untuk lolos dari jepitan dua iblis ini.
Matanya tertumbuk pada buntalan kain yang jatuh dari pinggang Puang Parungu saat bergulat tadi. Buntalan itu terbuka sedikit, memperlihatkan isinya: beberapa tabung bambu kecil yang tertutup rapat dan… sebungkus bubuk mesiu.
Senyum tipis dan nekat terbit di bibirnya yang pucat. Otaknya yang cerdik—warisan dari masa kecilnya sebagai anak pelabuhan yang sering mengakali pedagang kikir—mulai bekerja.
“Hei, Pasangan Iblis!” teriaknya tiba-tiba, suaranya lantang meski tubuhnya masih terduduk.
Kedua petarung itu berhenti sejenak, menoleh ke arahnya dengan tatapan heran. Mereka mengira pemuda itu sudah mati keracunan.
“Kalian memperebutkan kitab ini, kan?” Ia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Di tangannya, bukan kitab yang ia pegang, melainkan tabung bambu dan bungkusan mesiu milik si kakek yang ia sambar diam-diam saat merangkak tadi.
Cahaya bulan tidak terlalu terang untuk membedakan benda itu dengan gulungan lontara.
“Serahkan padaku, Nak! Akan kuangkat kau jadi murid!” bujuk Puang Parungu, matanya berbinar tamak.
“Jangan dengarkan dia! Serahkan padaku, akan kuberikan kenikmatan dunia sebelum kau mati!” rayu Daeng Bunga, suaranya mengandung ilmu pikat Gendam Asmara.
Pemuda itu menyeringai. “Kalian berdua sama saja. Sama-sama Kongkong⁶ kelaparan! Kalau aku tidak bisa memilikinya, tidak ada yang boleh memilikinya!”
Dengan gerakan cepat, ia melemparkan bungkusan mesiu itu ke arah api unggun kecil sisa perkemahan Barata yang masih menyala redup di kejauhan—yang baru terlihat olehnya.
Bukan, ia tidak melempar kitab. Ia melempar mesiu.
Tapi di mata kedua pendekar tua yang sudah dibutakan oleh ketamakan, itu terlihat seolah-olah buronan mereka membuang kitab pusaka itu ke dalam api.
“JANGAN!” teriak mereka berdua serempak.
Tanpa dikomando, Puang Parungu dan Daeng Bunga melupakan permusuhan mereka sejenak. Mereka melesat bersamaan ke arah api unggun itu, berlomba menyelamatkan “kitab” yang akan terbakar.
Pemuda itu tidak menyia-nyiakan kesempatan emas itu.
Begitu kedua musuhnya melompat menjauh, ia mengerahkan sisa tenaga terakhirnya. Bukan untuk lari menjauh, tapi untuk memanjat. Ya, memanjat. Ia tahu ia takkan bisa berlari lebih cepat dari mereka.
Dengan gerakan Cicak Merayap di Dinding, ia memanjat batang pohon beringin raksasa di belakangnya, menyembunyikan dirinya di balik rimbunnya dedaunan dan akar gantung di ketinggian yang memusingkan. Ia menahan napas, menekan hawa murninya sampai titik nol agar tidak terdeteksi.
Di bawah sana, terdengar ledakan kecil.
DUAARR!
Mesiu itu meledak saat menyentuh bara api, melontarkan abu dan pasir panas ke wajah kedua pendekar yang baru saja hendak menyambar benda itu.
“AAARGH! Mataku!” jerit Daeng Bunga.
“Kurang ajar! Kita ditipu bocah ingusan!” raung Puang Parungu sambil mengibaskan jubahnya yang terbakar.
Mereka berdua berdiri di tengah kepulan asap, wajah coreng-moreng, amarah meledak-ledak. Mereka menoleh ke tempat mangsa mereka tadi berada.
Kosong.
Jejak di tanah pun hilang, tersapu oleh angin ledakan.
“Cari dia!” perintah Daeng Bunga histeris, kecantikannya luntur oleh wajah yang bengis. “Dia pasti belum jauh! Kakinya lumpuh!”
“Aku akan mencincangnya!” sahut si kakek.
Mereka menyebar, berlari ke arah selatan dan barat, mengira pemuda itu melarikan diri menjauh.
Di atas pohon, di kegelapan yang aman, pemuda itu mengintip ke bawah. Jantungnya masih berdegup kencang, tapi senyum kemenangan tipis menghiasi bibirnya yang pucat. Ia menepuk dadanya pelan, merasakan naskah lontara yang asli masih aman di balik bajunya.
“Maaf, Puang Guru,” bisiknya dalam hati. “Muridmu harus menjadi sedikit licik malam ini. Kehormatan tidak ada gunanya bagi mayat.”
Malam semakin larut di Ale’ Mali’. Pertarungan babak pertama usai, tapi perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan Sang Penerus sadar, mulai detik ini, ia bukan lagi sekadar buronan. Ia adalah pemain dalam catur maut yang mempertaruhkan nasib seluruh dunia persilatan tanah Sulawesi.
Catatan Kaki:
- Pal: Satuan jarak lama (sekitar 1,5 km).
- Mappakasiri’: Tindakan yang membuat malu atau menjatuhkan harga diri orang lain/keluarga.
- Baju Bodo: Baju adat perempuan Bugis-Makassar, berbentuk segi empat, biasanya berlengan pendek dan transparan.
- Pakarena: Tarian tradisional yang lemah gemulai, sering menggunakan kipas.
- Peteppu’: (Peteppu’/Pettu) Putus atau patah; dalam konteks ini merujuk pada jarum yang mematikan seketika.
- Kongkong: Anjing.
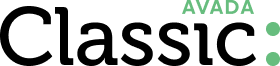

Leave A Comment